Kita ketahui bersama pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden RI Joko Widod...

Kajian mengenai pendidikan masih saja merupakan hal yang menarik untuk dianalisa dan dirumuskan keberadaannya. Dalam dunia ketiga, pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan. Ini menandakan bahwa pendidikan tidak hanya berbicara pada konteks bagaimana individu tersebut menjadi cerdas, tetapi juga berbicara bagaimana pendidikan mampu memperbaiki struktur pembangunan dalam negara tersebut.
Indonesia salah satu negara yang meletakan argumen tersebut. Pendidikan diharapkan mampu mendorong perbaikan - perbaikan ekonomi dalam kondisi krisis ini. Tidaklah berlebihan, jika dalam memformulasikan pendidikan yang baik perlu juga dipikirkan bagaimana upaya-upaya pemerintah di satu sisi dan lembaga-lembaga non pemerintah/swasta di sisi lain untuk mendorong agar pendidikan di Indonesia tetap berjalan.
Namun peran pihak swasta dalam pendidikan juga telah membawa sisi negatifnya yaitu sistem pendidikan telah terjerat pada sistem neoliberalisme yang justru mengakibatkan sisitem pendidikan mempunyai persoalan baru yang besar. Tetapi baiklah, sebelum penulis menjelaskan kaitan sistem pendidikan dengan neoliberalisme, maka penulis ingin menjelaskan dahulu esensi dari pendidikan itu sendiri.
Paradigma Pendidikan
Menurut Mansour Fakih dalam memahami pendidikan dikenal tiga paradigma pendidikan. Pertama, paradigma konservatif. Asumsi yang mendasari teori ini adalah pada dasarnya ketidaksejajaran dalam masyarakat adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan yang alamiah. Perubahan sosial melalui pendidikan dengan demikian bukanlah suatu yang harus diperjuangkan. Institusi pendidikan merupakan salah satu institusi yang melanggengkan hubungan yang tidak sederajat. Mereka yang bodoh, menderita, miskin, mengalami nasib begitu karena takdir Tuhan dan salah mereka sendiri. Paradigma ini menafikan bentuk-bentuk konflik dan kontradiksi yang amat mengangungkan harmoni sosial.
Paradigma kedua adalah paradigma liberal. Filsafat yang menopang paradigma ini adalah liberalisme, yakni suatu pandangan yang menekankan pada pengembangan, perlindungan hak dan kebebasan individu, identifikasi problem, dan upaya perubahan sosial secara inskrimental demi menjaga stabilitas jangka panjang. Dalam konsep ini tradisi liberal berakar pada tradisi barat yang mengagungkan individualisme. Pengaruhnya dalam pendidikan dapat dilihat dengan mencermati komponen-komponennya. Dalam pendidikan pengaruh paham ini dapat dilihat dari mengutamakan hasil unggul, prestasi, kemampuan akademik, yang semuanya dilakukan dalam suasana kompetitif. Kategori sekolah unggulan dan non-unggulan, rangkingisasi, insentif dan beasiswa hanya kepada mereka yang menonjol secara akademik adalah bentuk-bentuk kongrit bagaimana paradigma ini dijalankan.
Ketiga, Paradigma kritis. Dalam paradigma ini urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, membuat metodelogi dan muatan pendidikan yang bertujuan untuk menghancurkan ideologi dominan yang menghambat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Tugas utamamnya adalah menciptakan ruang dan media supaya sikap kritis terhadap sistem yang menindas dan tidak adil dapat tumbuh, disertai dengan upaya advokasi masyarakat yang paling tidak diuntungkan sehingga tercipta tatanan yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin berdiri netral dan objektif.
Sementara menurut Freirre yang berkaitan dengan pendidikan adalah kesadaran manusia. Ia menjelaskan bagaimana dehumanisasi telah menjadi bagian yang melekat pada pendidikan. Proses dehumanisasi terjadi akibat ketidaktahuan manusia yang berimplikasi pada struktur kesadaran. Ia mengklasifikasikan berbagai macam bentuk kesadaran mulai dari yang paling primitif sampai paling kritis.
Beberapa macam kesadaran itu terdiri dari Kesadaran magis, yakni kesadaran yang hanya berhenti melihat dan merasakan ketidakadilan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan tidak mampu melihat kaitan antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya, dalam dunia pendidikan, guru adalah kebenaran tunggal yang harus digugu dan ditiru oleh anak didik.
Kesadaran tahap berikutnya adalah kesadaran yang menekankan peranan dan aspek manusia sebagai penyebab timbulnya persoalan. Maka, pembenahan dan perbaikan atas seluruh bangunan masyarakat harus diarahkan pada manusianya sendiri. Anak didik harus diberi motivasi, dorongan, kursus , traning, dan sebagainya sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan sistem dalam masyarakat yang dianggap benar itu.
Selanjutnya adalah kesadaran radikal/kritis. Paradigma ini dalam pendidikan mencoba memperkenalkan cara-cara berpikir struktural dalam menganalisis masyarakat, lalu secara kritis mengajak anak didik untuk mampu memosisikan diri dalam struktur masyarakat dan mengidentifikasikan setiap bentuk ketimpangan dan ketidakadilan daam struktur tersebut.Yang ingin dicapai di sana adalah bagaimana merombak tatanan yang timpang tersebut dan mentransformasikannya dalam situasi yang lebih baik.
Tugas pendidikan yang menggunakan paradigma ini adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar anak didik terlibat dalam proses penciptaan struktrur yang fundamental baru dan lebih baik. Dalam pendekatan ini, konflik sosial bukanlah suatu yang ditabukan, bahkan secara mutlak dianggap penting. In the last analysis, conflict is the midwife consciousness.
Perjalanan Implementasi Pendidikan
Di samping memakai pendekatan-pendekatan teori di atas kami juga mencoba menganalisa fase-fase pendidikan di Indonesia sebagai titik awal/pintu masuk untuk mendalami penelitian kami. Pemetaan pendidikan tersebut kami bagi menjadi beberapa fase, yaitu :
Fase Orde Baru
Jaman orde baru, memikirkan format pendidikan di Indonesia ibarat mendayung di dua karang. Di satu sisi negara sebagai pelaksana dominan pendidikan membutuhkan tenaga-tenaga yang dapat menopang struktur sosial politik yang dibangunnya. Tetapi di sisi lain model seperti ini memberikan peluang pada proses dehumanisasi. Tak mengeherankan pada jaman orde baru, negara memberi kontrol yang sangat sentralistik pada aspek kehidupan manusia Indonesia, termasuk pendidikan.
Kontrol yang kuat tersebut semakin dilegitimasi dengan dibuat lembaga-lembaga mahasiswa yang merupakan kepanjangan tangan negara. Kemudian yang menarik disimak adalah pemaknaan terhadap pendidikan selalu mengalami pergeseran yang disesuaikan dengan strategi dan kebijakan yang disesuaikan oleh menteri yang pernah memegang di kabinet pada fase tertentu.
Dari dalil tersebut kita bisa mengajukan gugatan, apakah selama ini kebijakan dan strategi pendidikan di Indonesia tidak/ belum pernah diletakan pada arus utama (mainstream) di mana pendidikan dilakukan demi tujuan pendidikan itu sendiri (mendidik, membebaskan dari rasa ketidaktahuan) dengan fokus si anak didik? Ataukah justru pendidikan lebih berorientasi pada pembangunan, industrialisasi, iptek atau apapun namanya dengan fokus utama yang bernama Negara?
Apa yang kita persoalkan itu nampak pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada pemerintah, dimana yang selalu memetik buahnya adalah negara. Jika dikritisi kembali, pembebasan buta huruf dilakukan pertama-tama agar masyarakat secara efektif dapat menangkap pesan-pesan pembangunan dalam bentuk tulisan, kurikulum pendidikan yang selalu berubah-ubah, semata-mata karena pembangunan membutuhkan output pendidikan yang menguasai jenis keahlian tertentu. Tetapi perubahan tersebut acapkali kurang memperhatikan beban ekonomis yang harus ditanggung oleh pemakai pendidikan (masyarakat luas).
Jika asumsi yang mendasari alasan tersebut benar, lalu apakah mungkin dunia pendidikan mampu melepaskan diri dari kepentingan negara, sementara pada saat yang sama kita menyaksikan peran dominan negara yang sangat besar. Artimya, prinsip kebebasan sebesar-besarnya (prienciples of greatest equal liberity) dan prinsip perbedaan (difference principle), kesamaan adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).
Inti prinsip yang terakhir adalah bagaimana perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung atau mereka yang paling kurang memiliki peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.Prinsip keadilan John Rawls inilah yang dihancurleburkan dalam dunia pendidikan kita, di mana distribusi kesempatan yang berorientasi pada humanisasi dan pengembangan SDM.
Sementara menurut Herbert Marcuse menunjukan bahwa iptek sebagai sebuah derivasi ilmu pengetahuan (alam) tidak akan pernah mampu membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan. Ia hanyalah sebuah proyek histories (historical project) yang mencerminkan atau memproyeksikan kepentingan-kepentingan suatu masyarakat dari kelas-kelas yang berkuasa. Pada akhirnya seperti yang dikatakan Marcuse, bahwa pendidikan di Indonesia mau tidak mau menyerahkan kepalanya untuk diformat ulang dari waktu ke waktu agar ia selalu dapat selalu menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan negara.
Dunia pendidikan hidup di dua alam yang berbeda. Di satu sisi, ia harus tunduk pada logika kekuasaan yang menekankan bahwa pendidikan merupakan "pabrik" orang-orang pintar dan siap diserap di lapangan industri, disisi lain ia tidak mampu menolak fungsi etis dan normatif yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Disadari atau tidak, ini berdampak pada sistem pendidikan yang dehumanisasi juga berpengaruh pada proses belajar sehari-hari dimana anak didik dipandang hanya sebagai objek yang harus dicetak untuk kepentingan yang lebih besar yaitu industrialisasi.Fase Reformasi
Pada fase ini, terutama sejak (di) zaman pemerintahan Abdurahman Wahid sampai SBY sebenarnya sangatlah dilematis dan pelik. Karena persoalan pendidikan sangat terkait erat dengan persoalan ekonomi-politik nasional khususnya dan global pada umumnya.
Jika pada era orde baru negara begitu dominan pada pendidikan, tetapi ketika era Gus Dur, Megawati dan SBY di mana sebuah rejim yang dibebani hutang yang besar dan dipengaruhi keuatan global menjadi analisa tersendiri yang perlu dicermati.
Pada era ini, akibat kebijakan-kebijakan global/ neoliberalisme (meminjam istilah Anthony Giddens) turut mempengaruhi negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Untuk mengetahui dampak kekuatan global terhadap pendidikan di Indonesia, maka saya sedikit akan menjelaskan pokok-pokok yang akan terjadi jika kebijakan tersebut diterapkan.
Adapun pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Prinsip Pasar.
Membebaskan perusahaan "bebas" atau perusahaan swasta dari kewajiban-kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah (negara). Tidak peduli sebanyak apa kerugian sosial yang diakibatkannya. Keterbukaan yang lebih besar pada perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi, yang akan sangat menguntungkan semua orang. Ini mirip dengan kebijakan ekonomi "sisi-penawaran" dan "mengalir ke bawah"-nya.
2. Mengurangi Anggaran Belanja Publik Bidang Pelayanan Sosial
Ini dapat dilihat pada pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Mengurangi Dana Jaring Pengaman untuk Rakyat Miskin, dan bahkan dana pemeliharaan jalan raya, jembatan, pengadaan air. Kemudian atas nama pengurangan peran pemerintah. Tentu saja, mereka tidak menentang subsidi pemerintah dan keringanan pajak bagi dunia bisnis.
3. Deregulasi
Mengurangi peraturan pemerintah dalam segala hal yang bisa menurunkan keuntungan, termasuk dalam hal perlindungan alam dan keselamatan kerja.
4. Privatisasi
Menjual badan-badan usaha milik negara, barang-barang dan jasa kepada investor swasta, termasuk bank-bank, industri-industri strategis, jaringan rel kereta api, jalan-jalan tol, pembangkit listrik, sekolah-sekolah, rumah sakit dan bahkan air bersih. Walaupun biasanya dikerjakan atas nama efisiensi yang lebih besar, yang sering dibutuhkan, privatisasi terutama sekali berpengaruh dalam pemusatan kemakmuran yang lebih besar lagi ke tangan segelintir orang dan membuat masyarakat membayar lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhannya.
Nah, dalam kasus pendidikan menjadi semakin pelik. Misalnya untuk kasus perguruan tinggi, langkah-langkah yang coba diambil adalah sebagai berikut. Pertama, mengandalkan rencana menyeluruh dari negara. Kedua, menaikan biaya SPP. Ketiga, dengan cara mencari dana pada pemodal asing atau institusi swasta, entah berupa pinjaman. Keempat, dengan mendirikan unit-unit usaha, seperti pombensin, supermaket, wartel dan lain sebagainya.
Konsekuensi dari kebijakan ini adalah proses perguruan tinggi menjadi sangat lemah. Posisi perguruan tinggi dengan pemodal menjadi tidak seimbang. PT harus membuat dan mengajukan proposal-proposal proyek ,sebab jika tidak bagaimana ia mampu menghidupi biaya pendidikan yang hanya 35 % mendapat subsidi dari pemerintah.
Intinya, kebangkrutan negara yang disebut-sebut sebagai latar belakang munculnya PP 61/99 (tentang PTN dan badan hukum) adalah alasan yang tidak dapat diterima. Dalam kasus perguruan tinggi saja misalnya, pengurangan subsidi negara sebesar 35% adalah wujud dari tidak berdayanya negara dalam menghadapi gejala global tersebut.
Begitu pula dalam model-model pendidikan lainnya ( di bawah Perguruan Tinggi ) juga akan mengalami kesulitan yang sama, terlebih-lebih adalah Sekolah Dasar (SD). Sekali lagi ini semakin menjauhkan cita-cita pendidikan yang humanistik dan membebaskan dan pembudayaan (enculturation) nilai menurut konsep K Hadjar Dewantara.
Model Pendidikan Alternatif
Dalam upaya mencari sistem pendidikan yang lebih baik dan humanistik, (pembudayaan nilai) nampaknya sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemikir-pemikir yang serius masalah pendidikan ini.
Tokoh Pendidikan, Mudji Sutrisno, Syafi’i M’Arief, mencoba menjelaskan sistem pendidikan yang pernah diterapkan di Brazillia, merupakan kontektualisasi model pendidikan yang memberikan ruang efektif bagi kesadaran baru bagi anak-anak didik disana. Proses "menamai dan merajut makna" sekaligus merajut gambar dengan kesadarannya sendiri bergulat melalui perumusan, penggambaran, dan pembatinan sendiri sesuai dengan bahasa anak mendasarkan inti pendidikan pada pemekaran yang aktif dan hidup dari kesadaran anak.
Contohya, seorang anak yang berumur tiga tahun dan duduk di sekolah maternal awal, diajarkan untuk merekatkan benang tipis warna kuning dan benang tebal wol berwarna coklat untuk sekaligus menamai dan meresapi perbedaan kuning dan coklat, tebal dan tipis. Dalam proses ini anak menjadi aktif karena ia melakukan sendiri penempelan benang pada kertas dan memegang sendiri tipis-tebalnya dan melihat sendiri mana yang kuning dan mana yang coklat.
Guru hanya pemberi fasilitas dan kondisi yang memungkinkan si anak mengalami proses pemekaran berpikir. Ia tidak mendikte apalagi mencetak seragam pemikiran si anak.Guru sekadar menemani si anak dalam merumuskan dalam bahasa mereka apa yang dinamakan dunia. Maka pengaksaraan dan alfabetisasi menjadi sebuah proses pembukaan kesadaran anak lalu si anak sendiri manamai dengan kata-kata tertentu.
Dengan menamai sendiri dunianya dan memberikan makna atas realitasnya, si subjek berproses membentuk kemandiriannya. Otonomi yang dibahasakan dengan membuat kata, nama dan makna sendiri, sehingga melahirkan kepercayaan pada diri sendiri dan demikian si anak dapat mengedepankan dalam keunikan pribadinya masing-masing. Inilah yang dinamakan pendidikan yang humanistik.
Dalam realitas masyarakat, model pendidikan yang berdasarkan pada subjek akan senantiasa model pendidikan model "bank", (banking system).. Dimana model ini menganggap anak tidak mengetahui apa-apa, (botol kosong) sehingga pemaknaan atas realitas harus dilakukan oleh seorang guru. Dalam model pendidikan gaya bank alfabetisasi dan pemaknaan dilakukan oleh guru dan tidak pernah sampai menyentuh pada kesadaran anak, karena apa yang diberikan guru/pendidik bukanlah seperti dunia yang dilihat dan dihadapinya sehari-hari. Otak anak dianggap sama dengan kotak bank atau botol kosong yang beku dan statis.
Bentuk model pendidikan lainnya adalah yang pernah diterapkan di Mettray, Prancis. Sekolah yang menjadi kajian Michael Foucoult -seorang filsuf beraliran poistmodernisme. Sistem pendidikan ini mengenal disiplin dan hukuman, mengenal lima model pendidikan. Pertama, model keluarga, dimana anak didik dikelompokan dalam unit-unit kecil berdasarkan hubungan keluarga (kakak-adik). Kedua, model militer. Di mana setiap unit terkecil mempunyai model kepala sebagai komandan dan kepada setiap anggota dilatihkan latihan dasar kemiliteran dengan pemeriksaan kerapian dan kebersihan setiap hari. Ketiga, model bengkel kerja, yakni unit di mana pengawas dan pelatih bertanggung jawab melatih anggota yang lebih muda dan mengatur seluruh pekerjaan. Keempat, model sekolah, di mana pelajaran diberikan antara satu hingga satu jam setengah dalam satu hari. Terakhir adalah model pengadilan, di mana pelanggaran sekecil apapun dikenai hukuman. Dari kelima model ini diamati oleh Foucoult. Akhirnya ia menemukan individu-individu yang berlainan dalam setiap model tersebut.
Sesuai dengan zamannya, pendidikan juga terus bergulat mencari pembenahan-pembenahan agar keberadaannya mampu diterima dan dipraktekan semua orang.
Peran Swasta Dalam Pendidikan
Kondisi Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sangat dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu pula di bidang pendidikan. Artinya, ketika pemerintah hanya mampu mensubsidi pendidikan sebesar 35%, secara tidak langsung para praktisi pendidikan paling tidak dituntut untuk mencari biaya di luar subsidi tersebut.
Pihak swasta, sebagai salah satu bagian pilar ekonomi Indonesia, diharapkan ikut berperan memberikan andil dalam bidang pendidikan. Ini dimaknai bahwa pendidikan akan mengalami kemajuan atau tidak, peran swasta dituntut untuk berperan di dalamnya.
Dalam menghadapi teknoglobalisme dan teknonationalisme negara industrial mapan dan MNC ( Multinational Coorporation), negara periferal seperti Indonesia harus berkomitmen untuk menempatkan pembangunan teknologi dimana swasta menjadi bagiannya dan agenda nasional litas sektor termasuk pendidikan di dalamnya.
Ada beberapa bentuk peran swasta yang diterapkan di dunia dalam kaitannya dengan tehnologi. Jika japan incorporatied menempatkan kelompok perusahaan swasta sebagai pemain utama dalam pembangunan, lain halnya Eropa Incoorporated menempatkan perusahaan milik negara (BUMN) dengan nuansa walfare State yang signifikan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran swasta Indonesia dalam menunjang pembangunan yang berteknologi serta yang dapat menunjang mutu pendidika ?
Melihat data di atas, sepertinya Indonesia coorporated mensyaratkan partisipasi swasta dengan menkombinasikan perusahaan besar (konglomerat), perusahaan kecil-menengah (smaal/medium scale enterprise) dan sektor pemerintah yakni BUMN. Harus diakui perkembangan swasta di Indonesia sedikit banyak telah banyak membantu dalam hal pembangunan ekonomi Indonesia. Tetapi peran swasta dalam memacu pertumbuhan industri nasional dalam kerangkan pasar global belum begitu signifikan. Bahkan penelitian yang pernah dilakukan ekonom UGM bahwa peran swasta sangat kecil karena hanya menjadi "jago kandang" dan menikmati banyak dari proteksi pemerintah, sementara proteksi tersebut mengarah pada marketing empeding intervention.
Di sini penulis memberikan beberapa tawaran alternatif bagi swasta untuk berpartisipasi dalam pendidikan nasional. Dalam krisis ekonomi dimana pemerintah hanya mampu mensubsidi 35% terhadap pendidikan, peran swasta dapat dilakukan seperti pertama, memberikan beasiswa kepada siswa yang sedang mengenyam pendidikan. Tetapi beasiswa di sini bukan dalam pengertian yang sudah-sudah, di mana yang berprestasi berdasarakan nilai rapor atau rangking tertinggi akan mendapatkan kemudahan beasiswa, tetapi pemberian tersebut diberikan pada siswa yang memang berasal dari golongan ekonomi lemah. Model yang ditawarkan tersebut dengan asumsi bahwa sebagai pemerataan hak warga negara untuk mengenyam pendidikan yang sama. Disamping itu, tawaran tersebut dapat diterima sebagai konsekuensi ketika kebijakan global diterapkan yang berdampak naiknya biaya pendidikan ( baca : SPP).
Kedua, bersama pegiat pendidikan, memberikan dana untuk sekolah-sekolah dasar di desa tertinggal. Ini pernah diterapkan di Sekolah Dasar Mangunan Yogyakarta. Sekolah eksperimen yang dikhususkan untuk anak-anak yang berasal dari golongan lemah ini didirikan dan dibiayai dengan kerjasama antara pegiat pendidikan di satu sisi dan KPG (Kelompok Penerbit Gramedia) sebagai pihak swasta di sisi lainnya. Penulis beranggapan peran swasta dalam pendidikan sudah seharusnya melihat sektor tersebut.
Ketiga, bekerjasama dengan pegiat pendidikan menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang dalam pengembangan akademik. Lagi-lagi penulis beranggapan bahwa tunjangan ini dapat diberikan pada sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang benar-benar mempunyai program pemerataan pendidikan. Artinya, tunjangan tersebut dapat meringankan beban siswa golongan lemah dalam berproses dalam pendidikan. Pada prinsipnya maju-tidaknya pendidikan nasional setidaknya ada tiga kekuatan yang mempengaruhinya. Pemerintah, swasta dan sumber daya manusia. Dengan demikian, pihak swasta bersama pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang manusiawi. Artinya, anak didik tidak hanya dicetak untuk menjadi "pekerja" dari sebuah industrialisasi besar, tetapi lebih untuk mencetak kepribadian yang berwatak kemanusiaan.
Penulis percaya bahwa peran swasta sangat berpengaruh dalam memajukan pendidikan nasional. Ini diandaikan jika pihak swasta peka dan mampu bekerjasama dengan pemerintah serta pegiat pendidikan. Seperti halnya welfare State yang diterapkan di eropa, barangkali konsep pendidikan di Indonesia dapat dicoba dengan pendekatan teori tersebut. Pemerintah tetap berperan dalam hal pendidikan di satu sisi, tetapi swasta tetap diberi ruang di sisi lainnya. Dapatlah dipahami bahwa tidak adanya sentralisme pendidikan dari pemerintah, juga tidak adanya upaya liberalisasi dari pihak swasta untuk pendidikan. Ya, barangkali seperti sosial demokrasi di Eropa, konsep pendidikan tetap diletakan antara dua komponen yang telah dijelaskan di atas. Dus, pihak swasta tetap dapat memberi andil di dalamnya.
Perlawanan Menolak "swastanisasi" di Lingkungan Pendidikan
Dengan berkembangnya kebijakan neo-liberalisme di dunia internasional, termasuk di Indonesia menimbulkan penolakan-penolakan terhadap kebijakan tersebut. Penolakan konsep otonomi kampus versi negara juga terjadi di beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Misalnya di Universitas Gadjah Mada telah terbentuk KOMITE APIK (Komite Aliansi Pendidikan Indoneisa untuk Kerakyatan) yang teergabung dari beberapa kelompok di dalamnya. Seperti dari Majalah Balairung UGM, KPRP ( Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan ), DEMA (Dewan Mahasiswa ) UGM, KAPAK (Komite Aksi Pendidikan Anti Kapitalis), LSA ( Lingkaran Studi Alternatif) dan beberapa kelompok lainnya yang sepakat menolak konsep otonomi kampus versi negara.
Sedangkan di Jakarta, Universitas Indonesia telah juga membentuk jaringan dengan nama Pokja Uni yang juga mempunyai program yang sama. Begitu pula di bandung dengan komite-komite aksi di ITB dan di Bogor dengan komite-komite aksinya di IPB (Institut Pertanian Bogor). Untuk semakin memperkuat kelompok tersebut maka jaringan empat kota yang sepakat untuk membuat pendidikan "digadaikan' negara kepada pihak swasta akhirnya membentuk front. Demikian pula beberapa waktu lalu sejumlah LSM di Yogyakarta, menyampaikan somasi publik karena disinyalir sejumlah SMA di kota Yogyakarta melakukan praktek kapitalisasi pendidikan. Para Kepala Sekolah dinilai telah menyelewengkan semangat pendidikan, dan beralih pada praktek kapitaliasi pendidikan. Banyak pihak menilai kepala sekolah tidak memiliki "sence of crisis". Kapitalisasi pendidikan ini di pengaruh oleh semagat melegitimasi pendidikan, namun sebenarnya mutu pendidikan masih rendah.
Negara Telah Gagal ( Kasus Ujian Nasional): Sebuah Refleksi
Kebijakan Mendiknas mengenai perlu dilaksanakannya Ujian Nasional (UN) beberapa waktu lalu, mengundang banyak polemik. Dengan dalil UN bertujuan untuk mengukur "kompetensi nasional" siswa pada mata pelajaran yang ditentukan dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan. Sangat jelas, bahwa dasar pertimbangan perlu dilaksanakannya UN, untuk mengukur kompetensi nasional (kognitif ) peserta didik semata, adalah sebuah kebijakan yang keliru dan Mendiknas telah melakukan kesalahan konstitusional
Ketika mengukur “kompetensi nasional” sebagai dalil, maka gugatan dibalik itu selalu muncul. Manakala dalam pelaksanaan UN itu penuh dengan “kecurangan dan ketidakadilan”, dan menjadi pertanyaan bagi publik, apakah kemampuan seseorang hanya diukur dari mampu menyelesaikan soal-soal UN. Kalau itu yang dijadikan barometer, maka negara kita telah gagal mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD45, sebab yang ditekankan di situ hanya hard skills (life skills), sementara soft skills tidak pernah dijadikan pertimbangan mutu pendidikan. Dan lebih “berdosa” lagi UN sebagai sebuah bentuk ketidakpercayaan dan tidak menghargai profesi guru sebagai pengajar, pendidik, pembimbing terutama bagi guru-guru yang tidak mengampu mata pelajaran yang tidak di UN-kan. Disisi lain bentuk kebijakan tersebut adalah sebagai sebuah bentuk supremasi negara atas sekolah. Maka dengan kebijakan itu, segala hal yang berhubungan dengan penilaian peserta didik yang menjadi otoritas guru dan sekolah menurut amanat UU No. 20/2003, sekadar sebagai pajangan.
Dalam perjalanannya dari waktu ke waktu UN tidak menjamin terhadap semakin meningkatnya mutu pendidikan di tanah air. Sebab kalaupun sebagai alat kontrol untuk memastikan kualitas (quality assurance) mutu pendidikan, namun tidak akan pernah berubah kualitasnya, jika infrastruktur pendidikan dan kesejahtraan guru tidak pernah diperhatikan. Memang dalam tataran pendidikan, UN merupakan salah satu instrumen penilaian pengetahuan akademik (kognitif), namun bukan satu-satunya, masih ada instrumen lainnya seperti aspek psikomotorik (vocational), aspek afektif ( sosial, emosional, spiritual dan moral). Singkat kata dua aspek terakhir ini menjadi inti sari dari pendidikan. Menurut Lowenfeld, pendidikan yang lebih banyak menekankan aspek akademik (rasionalitas), maka pendidikan itu tidak lebih sekadar transfer of knowledge, yang cenderung memuaskan aspek rasionalitas siswa yang disimbolkan dalam angka-angka yang tertera dalam rapor atau ijazah. Dalam sistem pendidikan yang demikian, out put pendidikan tidak menciptakan kehamonisan jiwa peserta didik (well balance education), dan pengembangan pribadi seutuhnya ( the whole personality). Oleh karena itu segi pikiran dan perasaan haruslah dibina secara seimbang, supaya kemampuan kreatif dan kecerdasan tiap individu dapat tumbuh dan perkembang seimbang. Pendidikan yang lebih menekankan aspek rasionalitas, maka anak didik menjadi sombong dan sosialisasi diri rendah. Transfer ilmu pengetahuan rasional begitu ditekankan dalam pendidikan sehingga dimensi lain pendidikan seperti dimensi etis, spiritual, sosial, dan emosioanl terlupakan. Akibatnya pendidikan kita menjadi berat sebelah, yang pada gilirannya melahirkan manusia-manusia yang tinggi kadar intelektualisnya, namun tanpa emosi dan jiwa sosial yang haus akan nilai-nilai human ( Ben Senang Galus, Kedaulatan Rakyat, 22 Juli 2004)
Melalui pendekatan tunggal rasionalistas sebagai tolok ukur keberhasilan peserta didik, maka sistem pendidikan kita dari tahun ke tahun tidak akan pernah membawa perubahan apapun pada kualitas anak didik. Anak didik a terpaksa diajarkan untuk menghafal seluruh isi mata pelajaran yang di UN-kan. Dengan demikian pendidikan kita membuat anak didik sebagai “mesin” dalam proses perkembangan yang automatis. Automasasi membuat peserta didik bukan lagi subyek yang otonom, melainkan obyek penelitian yang tertindas karena keseimbangan psikologisnya terguncang ketika norma-norma etos sosial, human, emotional, spiritual di jungkirbalikkan. Maka tidak heran kalau rasa empati, solidaritas sosial pada anak didik kita meluntur habis. Itulah gejala umum hasil pendidikan kita, dan karenanya menurut Darmaningtyas, pendidikan telah mengabaikan filososi pendidikan yakni memanusiakan manusia.
Dengan makin meningkatnya kompleksitas kehidupan, akibat dominassi ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap usaha pendidikan yang memperhitungkan semua komponen pembentukan watak manusia, adalah membantu manusia meningkatkan kemampuannya dan bahkan sudah merupakan sine qua non, demi untuk mengungkapkan martabatanya sebagai manusia sempurna. Namun penekanan yang berlebihan pada aspek kognitif dalam kompleksitas pendidikan, akan menyebabkan pudarnya atribut pengembangan the whole personality, dan dapat menjerumuskan anak didik kepada sikap hidup yang intelektualistik konservatif, dan bukan mustahil anak didik hanya dapat menirukan pola berpikir yang serba postulat, tanpa kemungkinan melakukan penjelajahan konseptual yang membuka peluang bagi “creative thinking” ( manusia cerdas) untuk menciptakan sesuatu yang baru.
Supremasi negara
Kebijakan Mendiknas dilaksanakannya UN sekaligus menandakan bahwa tidak ada lagi kontroversi masalah mempolakan pedidikan nasional. UN diharapkan bisa menjadi piranti untuk memotivasi siswa, orangtua siswa, para guru dan pihak sekolah untuk lebih memaksimalkan proses pembelajaran bagi peserta didik. Pada tataran ini, tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat akan terus mengajak sekolah untuk menunjukkan akuntabilitas, obyektivitas, dan transparansinya dalam menentukan kelulusan peserta didiknya. Sebagai wujud tanggungjawab sosial kepada masyarakat serta untuk membuktikan dirinya sebagai lembaga pendidikan. Mampukah sekolah yang masih berada di bawah bayang-bayang supremasi negara manyambut ajakan masyarakat.
Salah satu wujud kerja negara (pemerintah) dalam dunia pendidikan adalah sebagai penentu kebijakan. Pemerintah dalam hubungan ini berkewajiban sekaligus berhak untuk mengambil suatu kebijakan serta merekonstruksikan kebijakan pendidikan sebelumnya, yang mana tentunya dianggap kurang relevan. Artinya, persekolahan kita mau tidak mau tetap akan berada di bawah supremasi negara; alias berada di bawah penguasa politik atau bentuk lain represi negara menurut AJ Saputra..
Kalau mau jujur, kebijakan pemerintah mengenai pendidikian selama ini kurang bisa menjawab tantangan-tantangan universal pendidikian, kurang memecahkan masalah-masalah substansial pendidikan. Sekadar menyebut salah satu masalah, misalnya wacana permasalahan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan pola dan sistem evaluasinya yang sampai sekarang masih terus layak untuk dipertanyakan. Kurikulum dimaksud sangatlah memerlukan guru-guru dengan taraf hidup yang layak agar mereka memiliki dedikasi dan loyalitas untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerja. Selain itu, KBK juga membutuhkan insfrastruktur pendidikan yang sangat lengkap. Sudahkah kebutuhan ini dipenuhi? Permasalahan semacam ini menandakan wacana yang berkembang masih berkisar pada tataran dekonstruksi-dekosntruksi kebijakan sebelumnya. Artinya, ketika kebijakan sebelumnya dilihat tidak lagi relevan, kebijakan baru pun belum terpetakan secara jelas.
Di samping itu, validitas hasil evaluasi melalui UN akan sangat sulit dijadikan acuan untuk menstandarisasikan pendidikan nasional. Hal ini diakibatkan oleh beragamnya karakteristik demografi dan geografis para peserta didik yang tersebar diseluruh wilayah nusantara, apalagi jika dilihat dari ketimpangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam hal insfrastruktur pendidikan sekolah sebagai pendukung esensial dalam melakukan proses belajar mengajar. Maka alangkah bijaknya jika “proyek” UN bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, menambah sarana belajar, memberikan beasiswa kepada anak yang tidak mampu, biaya studi lanjut guru.
Dengan demikian, maka sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kembali kebijakannya agar “bencana” ini tidak terualang kembali pada tahun-tahun mendatang, dan memberikan kesempatan penentuan kelulusan siswa kepada pendidik dan sekolah masing-masing, (Kompas, 4 Juli 2006). Apalagi esensi UN telah disalahfungsikan dan telah menyalahi prinsip evaluasi belajar, sehingga sekaligus mengakibatkan pelanggaran pada otonomi sekolah. Kembalikan penilaian itu pada otoritas guru di sekolah, sekarang juga.
*Ben Senang Galus,staf Dinas Dikpora Prov. DIY
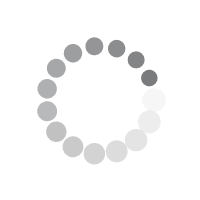




0 Komentar