Kita ketahui bersama pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden RI Joko Widod...

Pakar pendidikan H.G. Wells, mengatakan “ semakin tumpulnya etika sosial masyarakat tidak dapat tidak karena semakin suburnya praktek anomali dalam sistem pendidikan, sebagai salah satu sebab kemungkinan”. Demikian hipotesis H.G. Wells dalam laporan hasil penelitian dengan judul “ The Catastrope of Education, 1981, pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Penelitian H.G. Wells didorong atas dasar gejala ketidakberesan dalam sistem sosial, sistem pemerintahan, pendidikan pada negara berkembang. Kalau saja H.G. Wells itu benar, maka kita tidak perlu sakit hati atau dengan kata lain sia-sialah guru-guru atau dosen-dosen kita mengajar anak-anak kita, karena toh pada akhirnya pendidikan menghasilkan manusia mentalitas korup, tidak jujur, suka rampok. Bahkan gejala ini sudah menjalar sampai kepada lembaga agama, yang diyakini mempunyai kekuatan menolak segala bentuk anomali dalam masyarakat. Mestinya sekolah/kampus adalah tempat dimana anak-anak menemukan kegembiraan dan kebahagiannya. Di sana anak-anak belajar tentang kejujuran, belajar tentang etika dan moral, belajar menjadi dirinya. Di sana anak-anak memperoleh perlindungan dari ancaman-ancaman, di sana mereka belajar tentang demokrasi. Pokoknya sekolah adalah tempat memanusiakan manusia merdeka.
Namun dalam praktek justeru sebaliknya. Di sekolah anak-anak menjadi muram, sedih, takut menghadapi guru. Di sekolah anak-anak kehilangan kegembiraan dan terasing dari sesama teman. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi anak-anak yang hidupnya diwarnai dengan bermain. Di sekolah juga anak-anak sudah mulai resah, tak tahu nasib apa yang bakal menimpanya di masa depan.
Prof. Kurt Singer, dalam bukunya “Jika Sekolah membuat Sakit”, 2000, membeberkan panjang lebar gejala anomali pada pendidikan kita. Menurut Singer sekolah bukan lagi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Sistem pendidikan sekolah mau tak mau menjadikan guru sebagai agen yang mengawasi, menindas dan merendahkan martabat para siswa/mahasiswa. Sekolah menjadi lingkungan penuh sensor yang mematikan bakat dan gairah anak untuk belajar. Pekerjaan dan kewajiban sekolah menjadi diktator yang memusnahkan kemampuan anak untuk belajar menjadi dirinya. Sekolah/kampus bukan lagi tempat untuk belajar melainkan tempat untuk mengadili dan merasa diadili. Kurt Singer menyebut pendidikan sekolah kita yang mengakibatkan kegelisahan dan ketakutan itu, sebagai Schwarzer Paedagogic (pedagogi hitam).
Gejala anomali dalam pendidikan, setidak-tidaknya ada tiga faktor sebagai sebab. Pertama, semakin banyak guru berperan sebagai komandan lapangan tempur, yang tidak mengenal kata maaf. Kedua, sistem sekolah lebih mendekati model pendidikan penjara, anak-anak tidak pernah diajar tentang kebebasan berpikir, bergaul dan memiliki perasaan sosial dengan temannya. Sistem sekolah sengaja mengkotak-kotakkan anak yang bodoh dan yang pintar ( jalur akselerasi atau pertimbangan kaya dan miskin). Ketiga, guru atau dosen benyak mengambil jalan pintas dalam hal jual beli nilai atau mengajar/membimbing siswa/mahasiswa asal-asalan, sehingga siswa/mahasiswa kita tidak lebih sebagai “ tahu sepotong-sepotong mengenai sepotong-sepotong”.
Disamping itu sadar atau tidak pendidikan kita akan bersifat kodian atau belum tuntas, artinya masih kurang memberi perhatian kepada pengembangan individualitas yang mandiri. Hampir seluruh kegiatan di sekolah atau kampus belum banyak usaha nyata untuk menumbuhkan minat siswa/mahasiswa untuk cinta kepada kerja dan kerja keras. Mentalitas jalan pintas rupanya sejalan dengan budaya bangsa kita, budaya trobosan, budaya menjilat pimpinan, budaya mediokritas. Di kalangan siswa/mahasiswa budaya ini cukup tumbuh subur, seperti budaya menyontek, budaya plagiat, penelitian fiktif, budaya malas berpikir, budaya malas berdiskusi, budaya malas menulis, budaya suka jalan pintas. Oleh karena itu sekolah/kampus sejak dini perlu diajarkan bekerja keras dan jujur menurut kesanggupannya dan dijauhkan dari kebudayaan babu (babysiting culture). Sebab menumbuhkan warisan kerja keras dan jujur akan sulit tumbuh dalam kebudayaan babu. Pemikiran ini berawal dari suatu sintesa bahwa pada akhirnya pendidikan itu tidak akan bermanfaat apabila menghasilkan “ babysiting culture”.
Visi pendidikan masa depan harus jelas dan setidak-tidaknya tetap menghasilkan manusia apa yang disebut “ theologicalsynergism”. Artinya, pendidikan tidak menghasilkan manusia robot tanpa tuhan, pendidikan tetap menghasilkan manusia mengakui adanya kekuatan ilahi yang mengatur kekuatan jagat raya, yang berarti pula pengakuan terhadap keterbatasan iptek (keserasihan antarrasio dan alam semesta, antarmanusia dan tuhan, mengharmoniskan moral dan teknologi). Dengan demikian pendidikan kita tidak hanya mengurus bagaimana supaya manusia jadi pintar, tetapi lebih menampilkan sosok yang humanis.
Otonomi pendidikan sebagai jawaban atas inequty dan inequality atas sistem pendidikan. Disatu sisi otonomi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini berarti pemberdayaan sekolah sebagai masyarakat belajar (learning society) harus lebih dioptimalkan. Jika otonomi pendidikan sudah berjalan dengan baik, maka kemungkinan gejala anomali atau pedagogi hitam dalam praktek pendidikan akan semakin tereduksi, karena adanya kontrol yang sangat ketat dari masyarakat ataupun pers. Tugas pendidikan setidaknya mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah lama hilang dan tetap mempertahankan fungsinya sebagai garda depan pengajaran nilai, kejujuran, moral, etika sosial, sehingga terwujudlan manusia Indonesia yang bermoral tinggi, tanggungjawab, dan suka bekerja keras.
Keterlibatan masyarakat atau pers sebagai mitra sekolah akan sangat membantu perbaikan manajemen sekolah. Dan seluruh kegiatan pendidikan masa depan harus mengakomodir persoalan substansi yakni basic competency, yakni kombinasi antara academic competency dengan moral competency. Pada tingkat yang lebih tinggi kepala sekolah sebagai pilar kemajuan sekolah berperan menjadikan sekolah sebagai “ learning organization” yang senantiasa respons terhadap perubahan yang terjadi pada tingkat makro.
Dalam banyak hal keberhasilan pendidikan diukur sampai seberapa jauh pendidikan menunjang tingginya moral suatu bangsa serta pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu cukup beralasan jika Gestener, dalam Tilaar, mengatakan bahwa, permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan bukannya tidak adanya kemajuan yang dicapai, tetapi kemajuan tersebut belum dapat mengimbangi perubahan atau kemajuan di bidang lain.
Sebagai learning organization, sekolah dituntut mampu merumuskan tujuan atau program secara terukur. Keterukuran dalam penentuan program merupakan pedoman bagi guru dan kepala sekolah sendiri menjalankan fungsi dan alokasi dana. Realokasi dana dapat dilakukan dalam keadaan contingency, tetapi masih dalam batas pencapaian tujuan sekolah tidak akan terjadi kerugian ganda, yakni hilangnya energi yang terbuang percuma, hilangnya investasi yang semakin sulit dan langka, rasa ketidakpuasan karena jarak besar antarharapan dan hasil yang dicapai.
Demokratisasi pendidikan semacam ini adalah dasar yang tidak boleh ditawar dalam kehidupan bangsa beradab. Maka janganlah kita bermimpi demokrasi, kejujuran, bekerja keras, menghargai karya sendiri, menghargai pemikiran orang lain, dan lain sebagainya, akan dengan sendirinya terjadi jika tidak mengusahakan suatu sistem pendidikan demokratis, yang membebaskan manusia untuk dapat menjadi dirinya, dan dengan demikian juga menghargai orang lain untuk dapat menjadi dirinya.
Piranti Pengembangan SDM
Pendidikan sebagai salah satu piranti ( means) pembangunan SDM, harus secara jelas berperan membentuk peserta didik menjadi asset bangsa, yaitu SDM yang dengan keahlian profesional yang dimilikinya dapat menjadi produktif dan berpenghasilan, serta mampu menciptakan produk unggul industri Indonesia yang siap menghadapi persaingan di pasar global. Keahlian profesional yang harus dikuasai pada dasarnya mengandung unsur ilmu pengetahuan, teknik, dan kiat ( arts). Unsur ilmu pengetahuan dan teknik dapat dipelajari sendiri, sedangkan unsur kiat adalah suatu yang tidak diajarkan, tetapi dapat dikuasai melalui proses pembiasaan (habit forming ) dan internalisasi. Unsur kiat yang menjadi faktor utama penentu kadar keprofesionalan seseorang, hanya dapat dikuasai melalui cara mengerjakan langsung pekerjaan pada bidang profesi itu sendiri, karena itulah tumbuh suatu ukuran keahlian profesional berdasarkan jumlah pengalaman kerja.
Globalisasi perdagangan dan lebih luasnya bernuansakan kondisi pasar bebas merupakan suatu tatanan dunia baru hasil dari rekayasa masyarakat antarbangsa, guna menciptakan suatu kondisi interaktif perdagangan dan atau perekonomian maupun budaya yang relatif lebih bebas tanpa pembatasan rigiditas oleh aturan-aturan suatu negara.
Dalam konteks pasar bebas, pendidikan tetap diyakini keutamaannya karena berfungsi: memajukan ekonomi dan teknologi, mewujudkan dan memperteguh rasa kebangasaan dan menyelenggarakan suatu negara modern. Bila kemajuan tekonologi, ekonomi, keberbangsaan, dan kebernegaraan merupakan sebagian hajat pembangunan, jelas bahwa pendidikan ditafsir sebagai upaya penumbuhkembangan segenap potensi manusia. Ada keyakinan bahwa dengan pendidikan manusia dapat mengejawantah dalam wujud yang lebih bermutu. Bermodal pendidikan yang baik manusia mampu menyerap, mengembangkan dan meneruskan anasir-anasir wigati kebudayaan masyarakat.
Masalahnya kendati berbagai kemajuan telah dicapai, tidak berarti bahwa model program pendidikan sekarang dapat dipertahankan. Dalam pendidikan dasar, misalnya belum menunjukkan hasil yang meyakinkan. Selain itu, ditengarai bahwa, motivasi, kesadaran dan minat dan daya serap pelajaran sekolah dasar masih rendah. Belum lagi kecenderungan umum mereka untuk merasa jenuh, baik karena materi maupun proses pembelajarannya yang menekankan model banking system, (termionologi Paulo Freire), yang cenderung membosankan siswa. Karena itu tidak mengherankan bila angka putus sekolah menunjukkan prevalensi cukup tinggi. Program pembelajaran untuk peningkatan pendapatan dan mata pencaharian (life skills) cenderung kurang tersentuh oleh pendidikan kita. Dengan mempertimbangkan prioritas pada wajib belajar pendidikan dasar, keterabaian program belajar untuk peningkatan pendapatan dan mata pencaharian memang bisa dimaklumi. Numun bila kecenderungan ini terus terjadi, bukan tidak mungkin pendidikan kita tidak bisa berperan banyak dalam menyongsong era globalisasi pendidikan. Karena itu, kaharusan untuk mendekonstruksikan kembali makna pendidikan sebagai “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran” harus dilakukan. Dalam semangat meraih masa depan itu, pendidikan tidak boleh lagi terpasung dalam kegiatan pengajaran dan orientasi waktu sekarang semata. Tanpa kegiatan bimbingan dan latihan berorientasi ke depan, pendidikan justeru kehilangan makna dan jati diri sebagai penyedia layanan belajar yang luwes dan responsif terhadap kebutuhan individu, masyarakat dan pembangunan nasional.
Walhasil rancangan bangun program pendidikan harus menyertakan bimbingan dan latihan kewirausahaan, bukan sekadar sebagai bumbu untuk pengajaran akademik, melainkan sebagai bagian dari menu utamanya. Paling tidak, filosofi dasar, lingkungan belajar, pola ganjaran, dan pola kepemimpinan pendidikan harus dirancang ulang agar konduktif bagi tumbuh kembang motivasi berprestasi dan semangat kewirusahaan di kalangan peserta didik. Secara umum pemahaman kita tentang pendidikan belum berhasil mengubah persepsi dan pola pikir para pelaku pendidikan. Semula sangat kuat adanya kecenderungan anggapan bahwa dunia pendidikan dan dunia kerja merupakan dua hal yang berbeda, dimana keduanya berjalan pada jalurnya masing-masing dengan didasari perspektif yang berbeda; dunia pendidikan cenderung berpikir dari segi kepentingan pendidikan, sebaliknya dunia kerja cenderung berpikir dari segi kepentingan ekonomi.
Saat ini wawasan dan pola pikir kalangan pembina dan pelaku pendidikan, mulai dari pusat hingga tingkat pelaksana, cenderung beranggapan bahwa pendidikan merupakan bagian terpadu dari pengembangan sumber daya manusia dan tidak ada lagi kesan melaksanakan “ pendidikan demi pendidikan”. Mereka tidak lagi merasa “paling berhak, paling tahu, dan paling bisa” melaksanakan pendidikan. Sudah tumbuh kemauan dan keberanian membuka diri bahkan mengundang dunia usaha dan industri untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Hal ini sejalan dengan arah pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dewasa ini, yang pada reformasi pendidikan yang sedang dilaksanakan dewasa ini, yang pada pokoknya dimaksudkan untuk menghilangkan jarak diantara kedua dunia tersebut sehingga terjadi dialog yang mengarah kepada terjadinya transformasi dan integrasi.
Reinventing
Estimasi masyarakat terhadap rendahnya mutu pendidikan lebih disebabkan pendidikan kita telah mengalami disorientasi nilai, dan lebih mengedepankan pemenuhan keinginan politik ketimbang proses pencerdasan manusia. Aktivitas pendidikan hanya berkutat pada persoalan klasik yang memusatkan aspek rasional manusia. Transfer ilmu pengetahuan rasional ini begitu ditekankan dalam pendidikan sehingga dimensi lain pendidikan seperti aspek psikis, spiritual, aspek social dilupakan. Akibatnya pendidikan kita menjadi berat sebelah, yang pada gilirannya melahirkan manusia-manusia yang tinggi kadar intelektualnya namun tanpa emosi dan jiwa social yang haus akan nilai-nilai human. Itulah konsep pendidikan yang keliru selama beberapa dasawarsa yang kita terapkan pada anak didik kita, yang pada akhirnya pendidikan itu tidak akan bermanfaat, karena proses yang berjalan adalah robotisasi nilai. Gejala atau simpton pendidikan ini nampak pula dalam proses pendidikan yang secara singkat dapat dikatakan bahwa pendidikan kita hanya mendidik manusia untuk “tahu banyak hal dan pandai mengetrapkan sejumlah keterampilan teknis”.
Begitu kuatnya kita meletakkan proses yang keliru pada pendidikan, maka fungsi pendidikan ( sekolah) tak ubahnya sebagai penjara., yang seharusnya tempat dimana anak-anak menemukan kegembiraan dan kebahagiannya. Di sana anak-anak belajar berteman, bermain, menjadi dirinya, dan mengembangkan bakatnya. Proses yang begitu lama ini bermuara pada hasil pendidikan tidak pernah melahirkan manusia yang kritis dan cerdas. Pendidikan kita telah mengalami disfungsional karena isi pendidikan mengandung muatan-muatan nilai yang berakibat timbulnya kecemasan, ketakutan, kriminalitas, ketidakberdayaan, ketidakadilan, kesombongan, anaomali, dan sebagainya. Bahwa saintisme, pendewasan teknologi sebagai nilai mutlak, materialisme merajalela, kemerosotan mental dan moral, ketidakadilan social yang meluas, kekerasan merajalela, dan sebagainya, menjadi pilihan dan merasuk serta membantin pada sebagian masyarakat kita, tidak dapat tidak karena proses pendidikan yang keliru sebagai salah satu sebab kemungkinan. Walau demikian minornya penilaian orang terhadap proses/mutu pendidikan kita, sisi positifnya tetap ada, yakni lembaga pendidikan merupakan lembaga social yang paling arkais manakala masyarakat begitu dinamis dan rentan terhadap perubahan, fungsi pendidikan tetap sebagai “ watchdog” terhadap perubahan yang keliru. Sebab dengan memperoleh pendidikan yang secukupnya masyarakat kita akan tetap beradap dan menjadi merdeka pikiran dan batinnya ( konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara).
Dalam konsep Ki Hadjar Dewantara, lembaga pendidikan merupakan institusi social yang sangat menentukan kemajuan dan peradapan bangsa. Sulit dibayangkan, bangsa primitif menjadi beradab dan bisa bersaing dengan bangsa lain jika tidak tanpa melalui pendidikan yang bermutu. Oleh sebab itu pengelolaan pendidikan ke depan adalah perlunya reinventing pendidikan, yakni: 1)menempatkan peserta didik menjadi subyek dari agen perubahan untuk membebaskan dirinya dari isolasi peradaban dan pragmatisme intelektual. 2) Meletakkan kerangka konspetual pendidikan etis berbudaya Indonesia pada porsi yang lebih sehingga proses enkulturasi pendidikan bisa menemukan kembali wajah pendidikan kita yang berkebudayan Indonesia. Jangkauan jangka panjang yang kita harapkan adalah dari penyadaran menjadi pembebasan, dan dari pembebasan menuju humanisasi, baik personal maupun sosial, sehingga ia bisa melihat teman atau orang lain sebagai bagian dari ciptaan tuhan, bukan dianggap sebagai makluk kafir.
Dengan reinventing pendidikan mengantarkan manusia peserta didik bukan saja menjadi manusia yang pintar dan syarat dengan ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu menjadikan manusia peserta didik lebih humanis. Artinya pendidikan kita melahirkan kembali manusia peserta didik apa yang disebut “ humansynergism”. Hal ini dapat dijelas, meski pendidikan kita masih bersifat kodian, kurang memberi perhatian kepada pengembangan individualitas yang mandiri. Orientasi baru pendidikan kita ke depan dijauhkan dari mentalitas jalan pintas dan lebih banyak usaha nyata untuk menimbulkan minat peserta didik untuk cinta kepada kerja keras dan kejujuran, mengharagi kebudayaan sendiri, termasuk nilai-nilai local (local wisdom). Mentalitas jalan pintas rupanya sejalan dengan keengganan kepada kerja keras, budaya trobosan (nyontek, budaya fotokopi, malas berpikir) tetap saja hidup subur dalam budaya kampus/sekolah, yang pada akhirnya pendidikan kita hanya akan menghasilkan manusia Indonesia rasa segan dan enggan bertanggungjawab. Ia cenderung berorientasi ke atas, kepada otoritas, suatu sikap feodalisme dan paternalistic. Ia lebih suka diperintah, lebih suka disuruh menghafal, ia lebih suka menjadi buruh, menjadi babu (babysitting).
Menurut Mark Blaug begitu banyak informasi akan menimbun manusia sehingga manusia harus dapat memilih dan memanfaatkan untuk pengembangan pribadinya. Untuk itu konsep pendidikan menurut Blaug adalah kemudahan untuk memperoleh informasi. Kemajuan teknologi akan sangat membantu, meski kita tidak dapat mengatakan bahwa komputerisasi akan memecahkan seluruh problem pendidikan. Belajar dengan bantuan komputer akan membuka horizon yang sangat luas bukan saja dalam proses belajar, juga tentang konsep sekolah. Sekolah masa depan akan berubah sehingga akan lebih berupa “personalized learning center”. Komputer akan banyak mengambil alih prosesm belajar hal-hal yang wajib, tugas sekolah atau guru akan beralih kepada memperkenalkan dan membangkitkan persepsi mengenai nilai-nilai. Maka reinventing pendidikan kita ke depan antara lain juga harus menghasilkan manusia apa yang disebut “enculturationsynergism”. Artinya, pendidikan itu tidak menghasilkan manusia robot tanpa budaya, pendidikan tetap menghasilkan manusia mengakui adanya kekuatan budaya yang mengatur kegiatan jagat raya, yang berarti pula pengakuan terhadap iptek (keserasihan antar akal dan alam semesta, antar manusia dan tuhan). Secara sederhana dapat dijelaskan pendidikan “bagaimana mengharmoniskan antar moral dan budaya, dimana manusia, mengakui adanya kekuatan moral yang mengatur kekuatan rasio, yang berarti pula mengagumi kebudayaan”. Dalam praktiknya proses pendidikan harus mengenalkan model pendidikan holistic, yakni, pendidikan moral, pendidikan social, pendidikan budi pekerti, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan kebudayaan,dan pendidikan mental. Dengan menerakan pendidikan holistic ini anak bangsa kita tidak saja menjadi pintar tapi juga menghasilkan manusia berbudaya.
Proses Pembudayaan
Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni, pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Kegiatan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara ketat dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan di luar sekolah, meski memiliki rencana dan program yang jelas tetapi pelaksanaannya begitu longgar dengan berbagai pedoman yang fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Pelaksanaan pendidikan dalam keluarga dilaksanakan secara informal tanpa tujuan yang dirumuskan secara baku dan tertulis. Dengan mendasarkan pada konsep pendidikan tersebut di atas, maka sesungguhnya pendidikan merupakan pembudayaan atau “enculturation”, suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Konsekuensi dari pernyataan ini, maka praktek pendidikan harus sesuai dengan budaya Indonesia, jika tidak, akan menimbulkan penyimpangan yang dapat muncul dalam berbagai bentuk goncangan-goncangan kehidupan individu pada anak didik kita.
Tuntutan keharmonisan antara pendidikan dan kebudayaan bisa pula dipahami, sebab praktek pendidikan harus mendasarkan pada teori-teori pendidikan dan giliran berikutnya teori-teori pendidikan harus bersumber dari suatu pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. Berbagai penyimpangan yang ada dalam masyarakat, misalnya membesarkan jumlah pengangguran, berkembangnya mentalitas jalan pintas, sikap materialistik, indivualistik, dominannya nilai-nilai ekstrinsik terutama di kalangan generasi muda, dari satu sisi bisa dikaitkan dengan kegagalan praktek pendidikan yang berkiblat ke Amerika. Dengan kata lain, praktek pendidikan yang kita laksanakan tidak atau kurang cocok dengan budaya Indonesia. Untuk itu, perlu dicari sosok bentuk praktek pendidikan yang berwajah Indonesia.
Pendidikan merupakan proses yang berlangsung dalam suatu budaya tertentu. Banyak nilai-nilai budaya dan orientasinya yang bisa menghambat dan bisa mendorong pendidikan. Bahkan banyak pula nilai-nilai budaya yang dapat dimanfaatkan secara sadar dalam proses pendidikan. Sebagai contoh di Jepang “moral Ninomiya Kinjiro” merupakan nilai budaya yang dimanfaatkan praktek pendidikan untuk mengembangkan etos kerja. Kinjiro adalah anak desa yang miskin yang belajar dan bekerja keras sehingga bisa menjadi samurai, suatu jabatan yang sangat terhormat. Karena saking miskinnya, orang tuanya tidak mampu membeli alat penerangan. Oleh karena itu dalam belajar ia menggunakan penerangan dari kunang-kunang yang dimasukan dalam botol. Kerja keras diterima bukan sebagai beban, melainkan dinikmati sebagai pengabdian. Selain semangat kerja keras, budaya Jepang juga menekankan rasa keindahan yang tercerminkan pada ketekunan, hemat, jujur dan bersih sebagaimana semangat Kinjiro diwujudkan dalam patung anak yang sedang asyik membaca sambil berjalan dengan menggendong kayu bakar di bahunya. Patung tersebut didirikan di setiap sekolah di Jepang.
Dalam kaitan ini perlu dipertanyakan adakah nilai-nilai dan orientasi budaya kita yang bisa dimanfaatkan dalam praktek pendidikan? Manakah nilai dan orientasi budaya yang perlu dikembangkan dan manakah yang harus ditinggalkan? Serangkaian pertanyaan tersebut menjadi agenda kita ke depan.
Tentang Penulis
*) Ben Senang Galus, lahir di Manggari, 22 Oktober 1961, alumni UAJY 1988, kini menjadi staf Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi. DIY. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif menulis di berbagai media cetak, baik lokal maupun nasional. Antara lain: BernasYogya, Kedaulatan Rakyat, Bali Post, Nusatenggara, Surya, Suara Karya, Sinar Harapan, Solo Post, Kompas, dan Jurnal ilmiah. aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional. Menulis di buku Keadilan dan Perdamaian, Dom Belo: Negarawan dan Pejuang HAM, editor Peter Tukan, terbitan KWI Jakarta, 1997. Hasil penelitian “Dampak Pembangunan Ekonomi Pasar Terhadap Kehidupan Sosial Budaya” (1995) dan “Integrasi Nasional Suatu Pendekatan Sosial Budaya di Indoneia” (1997), diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sampai dengan saat ini sudah menghasilkan karya tulis sebanyak 560 buah artikel baik di surat kabar maupun jurnal dalam dan luar negeri. Sedang menulis dua buah buku “Pendidikan di Negara Bencana” dan “Globlisasi, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan”. Selain PNS, penulis sebagai dosen luar biasa di beberapa peguruan tinggi di Yogyakarta, dan staf ahli di Lembaga Studi Kebijakan Publik Indonesia.
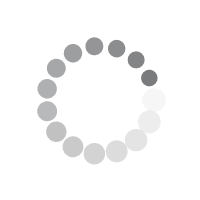




0 Komentar